Pendidikan Berbasis Kultur
pelajaran yang berjubel di sekolah menjadi tidak relevan lagi. kecerdasan tidak lagi diukur dari kenyataan bahwa seorang siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran dengan nilai 8 atau 10. Sebab, tiap orang punya karakter dan kecerdasan berbeda-beda. Howard Gardner membagi dalam delapan bidang kecerdasan.
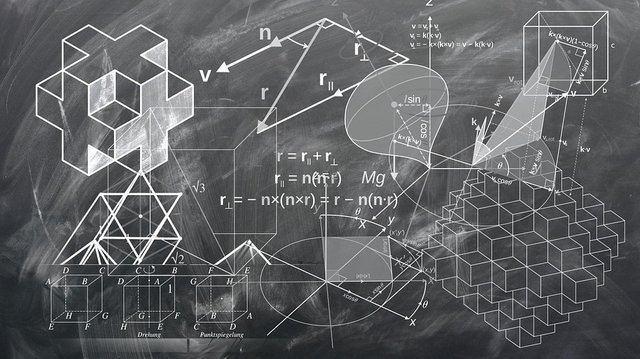
Ilustrasi: Pizabay
Kultur atau kebudayaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah (1) hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat; (2) keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya.
Filsuf Mudji Sutrisno (2008:6) merumuskan bahwa kebudayaan adalah gejala manusiawi dari kegiatan berpikir (mitos, ideologi, ilmu), komunikasi (sistem masyarakat), kerja (ilmu-ilmu alam dan teknologi), dan kegiatan-kegiatan lainnya. Atau, dalam bahasa Koentjaraningrat (1985:9), kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia.
Dalam konteks pendidikan, kultur berperan penting untuk melahirkan hasil seperti apa yang diinginkan diperoleh. Pendidikan yang mengadopsi kultur Barat tentu akan melahirkan manusia-manusia berkultur Barat. Begitu pula pendidikan yang mengadopsi kultur Indonesia, tentu akan melahirkan manusia-manusia berkultur Indonesia. Konsepsi "apa yang kita tanam itulah yang kita tuai" tentulah berlaku dalam segala lapangan kehidupan.
Pertanyaannya kemudian: apakah pendidikan kita sudah berbasis kultur Indonesia? Jika sudah, pertanyaan lanjutannya:
Indonesia yang mana? Indonesia kini dihadapkan pada persoalan nilai-nilai, karakter, yang makin longgar. Pendidikan kehilangan kekuatan untuk mencetak manusia-manusia berkarakter. Kualitas pendidikan lebih banyak ditentukan oleh nilai dalam arti sebenarnya (kuantitatif), bukan nilai dalam arti substansial (kualitatif). Dengan kata lain, kualitas sama dengan nilai 10.
Padahal nilai kuantitatif selalu menjadi perdebatan. Sejauh mana nilai itu menjadi representasi kualitas seseorang. Apakah seorang siswa yang lulus dengan nilai 9 otomatis menunjukkan bahwa ia manusia berkualitas. Sebaliknya, apakah seorang siswa yang nilainya cuma 6 otomatis digolongkan sebagai manusia tidak berkualitas. Dalam kerangka ini pula praktek ujian nasional bisa digugat.
Apalagi ketika merujuk pada teori kecerdasan mutakhir, yang oleh Howard Gardner (2007: 106), seorang psikolog dari Harvard University, disebut sebagai kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Ia membaginya dalam delapan bidang kecerdasan: kecerdasan linguistik, kecerdasan spasial, kecerdasan matematis, kecerdasan kinestetis, kecerdasan musik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis.
Dengan konsep ini, kecerdasan tidak lagi diukur dari kenyataan bahwa seorang siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran dengan nilai 8 atau 10. Sebab, tiap orang punya karakter dan kecerdasan berbeda-beda. Ada anak yang pintar matematika, ada yang pintar seni, ada yang pintar bahasa, ada yang pintar matematika, dan sebagainya. Mereka bisa disebut cerdas meskipun hanya menguasai satu bidang.
Justru kemampuannya dalam satu atau dua bidang itu akan menjadi keunggulannya yang bisa terus digali dan diasah. Pada gilirannya, itu akan menjadi benar-benar ahli. Jika seorang anak pintar matematika, hal itulah yang seharusnya terus dipertajam, sehingga pada saatnya ia akan menjadi ahli matematika. Bidang-bidang lain cukup diketahui dan dipelajari secukupnya saja. Begitu pula yang pintar sastra, pintar fisika, dan sebagainya.

Ilustrasi: Pixabay
Maka, pelajaran yang berjubel di sekolah menjadi tidak relevan lagi. Sudah saatnya pendidikan berorientasi pada spesialisasi dan minat setiap anak, bukan pada generalisasi. Hal-hal general cukup dipelajari sepintas lalu. Siswa lebih banyak dikasih tugas dan eksperimen-eksperimen sesuai dengan minat dan bidang kemampuannya. Jadi, tiap anak punya mata pelajaran pilihan sesuai minat dan bidang kemampuan masing-masing, di samping mata pelajaran reguler.
Sekilas, ini terlihat agak merepotkan. Ini mengingat kelas-kelas sekolah di Indonesia adalah kelas-kelas gemuk, bahkan sampai 40 siswa dalam satu kelas. Problemnya lagi-lagi soal sarana dan prasarana, ketersediaan guru, anggaran, dan sebagainya. Namun semua itu bisa dipecahkan jika hal ini menjadi sebuah kebijakan. Yang dibutuhkan kini adalah sebuah keinginan politik untuk melakukan redefinisi dan restrukturisasi pendidikan kita.
Sudah saatnya kita meninggalkan pendidikan yang berorientasi pada angka-angka. Pembenaran bahwa nilai kuantitatif adalah standar untuk mengukur kemajuan pendidikan sulit diterima di tengah maraknya percaloan, joki, pembocoran soal, dan sebagainya dalam ranah pendidikan.
Siswa, termasuk guru-gurunya, mati-matian mengejar nilai: belajar, menghafal, dan sebagainya. Setelah ujian selesai, hilanglah semuanya, tak ada yang tersisa. Proses belajar-mengajar didesain untuk bertarung dalam ring ujian, bukan sebagai bekal bagi anak-anak itu kelak menjadi manusia-manusia unggul dan mandiri.
Tak mengherankan pula jika kemudian pendidikan terjauh dari kultur. Selain karena sibuk dengan urusan mengejar angka dan kelulusan, juga karena pendidikan kita sangat sentralistik. Kurikulum diatur dari pusat, bukan dibuat di daerah. Padahal setiap daerah punya keunikan dan ciri khas masing-masing. Muatan lokal sekolah sangat sedikit.
Boleh saja kurikulum dibuat dari pusat sebagai standar umum. Namun seharusnya daerah diberi hak dan wewenang untuk memasukkan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan dan kultur daerah itu. Menjadi sangat bikin miris jika ada anak yang tahu tentang pahlawan nasional, tapi tidak mengenal pahlawan-pahlawan lokal di provinsinya. Mereka tahu tentang Borobudur, tapi tidak tahu ada tempat-tempat dan peninggalan penting di daerahnya.
Seharusnya, kurikulum bukanlah faktor penekan, melainkan sebagai petunjuk arah saja. Ia hanya menjelaskan garis besar dari sebuah proses pendidikan, bukan penentu yang detail dan rigid. Karena itulah, menjadi tidak relevan sistem kurikulum yang bertolak dari pusat. Apa yang dipikirkan para pembuat kurikulum di pusat belum tentu sesuai dengan kenyataan di lapangan, di tempat kurikulum itu dipraktekkan.
Kurikulum haruslah mengakar dari kebutuhan-kebutuhan riil di lapangan. Materi pendidikan tidak boleh hanya berada di menara gading, hanya mempelajari sesuatu yang jauh dari kehidupan nyata. Memang ada pretensi agar otak dan logika terasah, pikiran tertajamkan. Tapi bukan berarti peserta didik lebih banyak dijejali dengan materi-materi yang membuat dia terasing dari kehidupannya.
Pendidikan berbasis kultur akan membuat seseorang menjadi memahami dan apresiatif terhadap kehidupan di sekelilingnya, sekaligus akan membuat mereka bisa menyelesaikan persoalan-persoalan aktual. Sehingga, ia tidak menjadi orang gagap selepas dari bangku sekolah. Ia sudah punya bekal yang cukup untuk terjun dalam masyarakat.

Ilustrasi: Pixabay
Dengan demikian, apa yang disebut pendidikan berkarakter pun makin kuat. Sebab, pendidikan berkarakter bukan hanya pendidikan yang sarat ajaran moral, juga pendidikan yang memberi kesempatan kepada siswa untuk mengapresiasi dan menghargai kehidupan di sekelilingnya dan kehidupan aktualnya. Itulah sebenarnya tujuan penting pendidikan: mencetak manusia yang mampu menghadapi tantangan zaman. *
MUSTAFA ISMAIL
musismail.com
@musismail
TUlisan ini pernah dimuat di rubrik Ide Koran Tempo, 19 Jun 2011
Posted from my blog with SteemPress : http://musismail.com/pendidikan-berbasis-kultur/
Please Upvote➜https://steemit.com/christianity/@bible.com/verse-of-the-day-revelation-21-8-niv
Please Upvote➜https://steemit.com/christianity/@bible.com/verse-of-the-day-revelation-21-8-niv